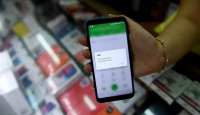Muslim Nge-Friend di Era Strawberry Generation

Menjadi muslim moderat bagi pria karib disapa Bamsoet, harus selalu meminjam istilah filosof Bertrand Russell, diinspirasi oleh kekuatan cinta dan dibimbing ilmu dalam memaknai setiap nafas kehidupan. Dengan kata lain, menjadi muslim di ruang publik mesti didasari oleh kesadaran literasi yang melekat dalam setiap jiwa manusia.
Mereka selalu merindu pada Sang Pencipta yang Mahacinta. Sifat-sifat keagungan Tuhan itu harus ditunjukan pada kelembutan cinta-Nya. Puncak dari proses itu, tiada lain, adalah akhlak mulia: berdamai dengan alam, menebar kebajikan, merawat keragaman, dan merayakan kemanusiaan. Mereka adalah generasi “tengah-tengah” (wasathon). Di benaknya hanya memancar sifat-sifat tawasuth (moderat), tawazun(seimbang), adil, dan tasamuh (toleran). Itulah yang dalam istilah NU disebut sebagai “Islam Nusantara”.
Sedangkan dalam istilah Nurcholish Madjid, karakter “muslim moderat” itu dirumuskan dalam sebuah adagium: “keislaman, keindonesiaan dan kemodernan”. “Api Islam” yang menjadi jalan visoner seorang Cak Nur jelas ingin mensenyawakan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dalam sebuah bingkai rasionalitas sebagai respon terhadap alam pikiran modern. Mereka tak pernah ekstrim, baik dalam pikiran maupun tindakan. Seorang muslim sejati selalu merawat dan menghargai eksistensi kelompok lain. “Islam itu ramah, bukan marah”.
Membumikan Pancasila, Melawan Radikalisme
Dalam jiwa “muslim moderat” variabel kebangsaan itu menjadi sangat penting. Hal itu, antara lain ditunjukkan dengan bukti mereka menerima Pancasila secara kaffah. Maka, bagi para punggawa “muslim moderat” persoalan Pancasila sudah selesai; tidak ada keraguan sedikit pun di benak mereka tentang Pancasila sebagai dasar negara, ideologi maupun falsafah hidup bangsa. Sikap NU, Muhamadiyah, HMI sebagai kampium muslim moderat, misalnya, menjadi bukti nyata.
Namun demikian, tantangan fundamentalnya adalah: bagaimana membumikan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi karakter bangsa yang hidup dan kuat, baik sebagai karakter moral maupun kinerja. Karena nilai-karakter bukan saja menentukan eksistensi dan kemajuan seseorang, melainkan pula eksistensi dan kemajuan sekelompok orang, seperti sebuah bangsa.
Dalam Amanat Proklamasi, 17 Agustus 1956, Bung Karno mengingatkan pentingnya bangsa memiliki kekuatan karakter yang dibangun atas dasar kedalaman penghayatan atas pandangan hidup bangsa. “Bangsa Indonesia harus mempunyai isi-hidup dan arah-hidup. Kita harus mempunyai levensinhoud dan levensrichting. Bangsa yang tidak mempunyai isi-hidup dan arah-hidup adalah bangsa yang hidupnya tidak dalam, bangsa yang dangkal, bangsa yang cetek, bangsa yang tidak mempunyai levensdiepte samasekali. Ia adalah bangsa penggemar emas-sepuhan, dan bukan emas batin. Ia mengagumkan kekuasaan patung, bukan kekuasaan moril. Ia cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Ia kadang-kadang kuat, tapi kuatnya adalah kuatnya kulit, padahal ia kosong mlompong di bagian dalamnya.”
Kata-kata Bung Karno di atas sangat berenergi dan menggetarkan. Renungannya mendalam: mencerminkan kekuatan pikir dan batin. Pesan moralnya sangat tegas dan selalu aktual: jika bangsa ini ingin keluar dari krisis dan kemudian tumbuh menjadi bangsa yang besar dan maju serta berkeadilan, maka satu-satunya cara yang paling tepat adalah kembalilah kepada Pancasila sebagai rel perjuangan bangsa. Jadi, Pancasila adalah strategi kebangsaan yang mesti kita rawat, pupuk, dan bumikan—terutama kepada anak-anak muda calon-calon penerus pemimpin bangsa.
Sekali lagi, untuk memberi isi (nilai) dan arah hidup, Bamsoet menegaskan jiwa bangsa ini perlu dibangun dengan kesengajaan menyemai kembali nilai-nilai keindonesiaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pembudayaan nilai-nilai dan moralitas Pancasila. Ibarat pohon, perkembangan sejarah bangsa yang sehat tidak bisa tercerabut dari tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial-budaya, sistem pemaknaan (ideologi), dan pandangan dunianya sendiri.
 JPNN.com
JPNN.com